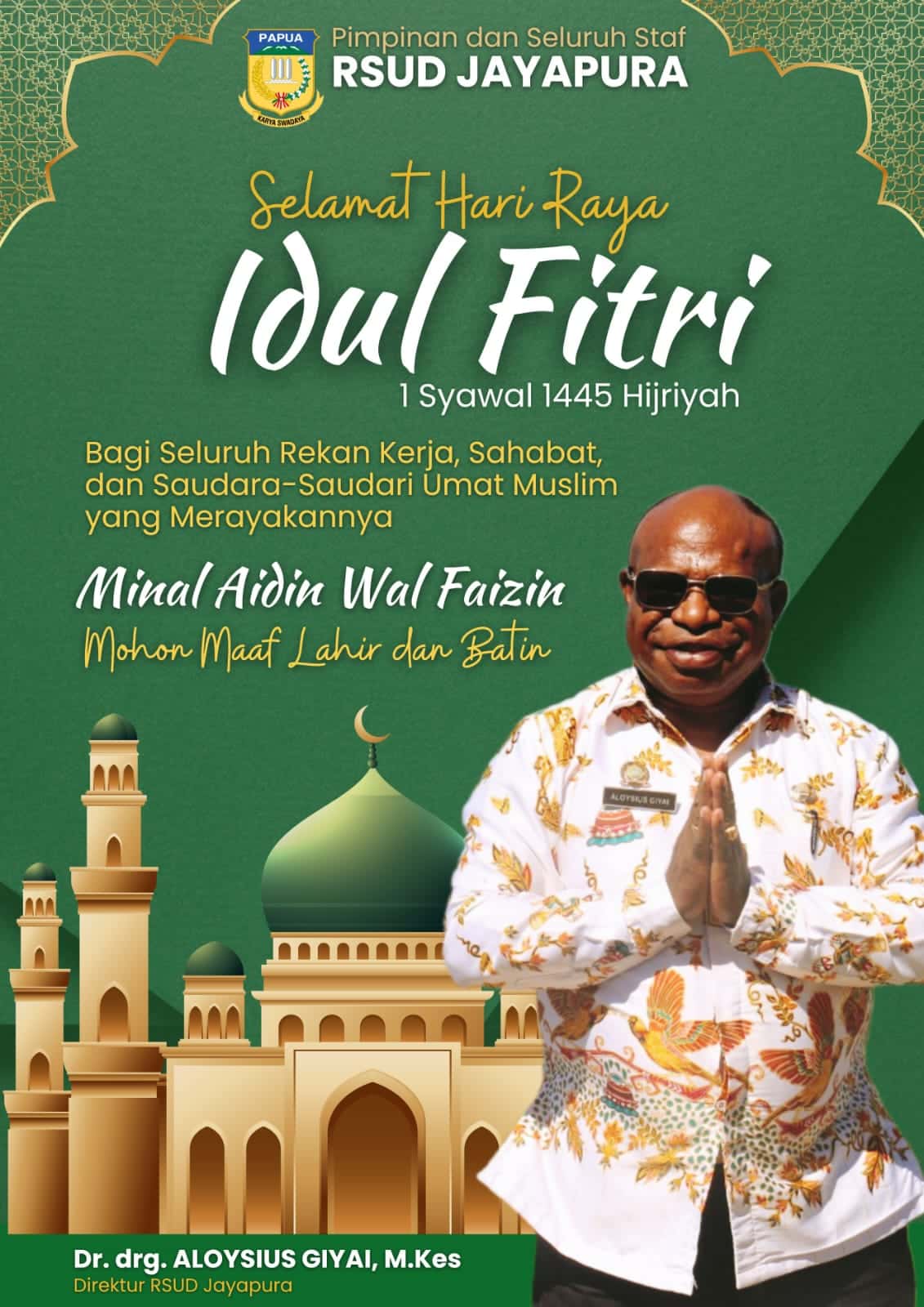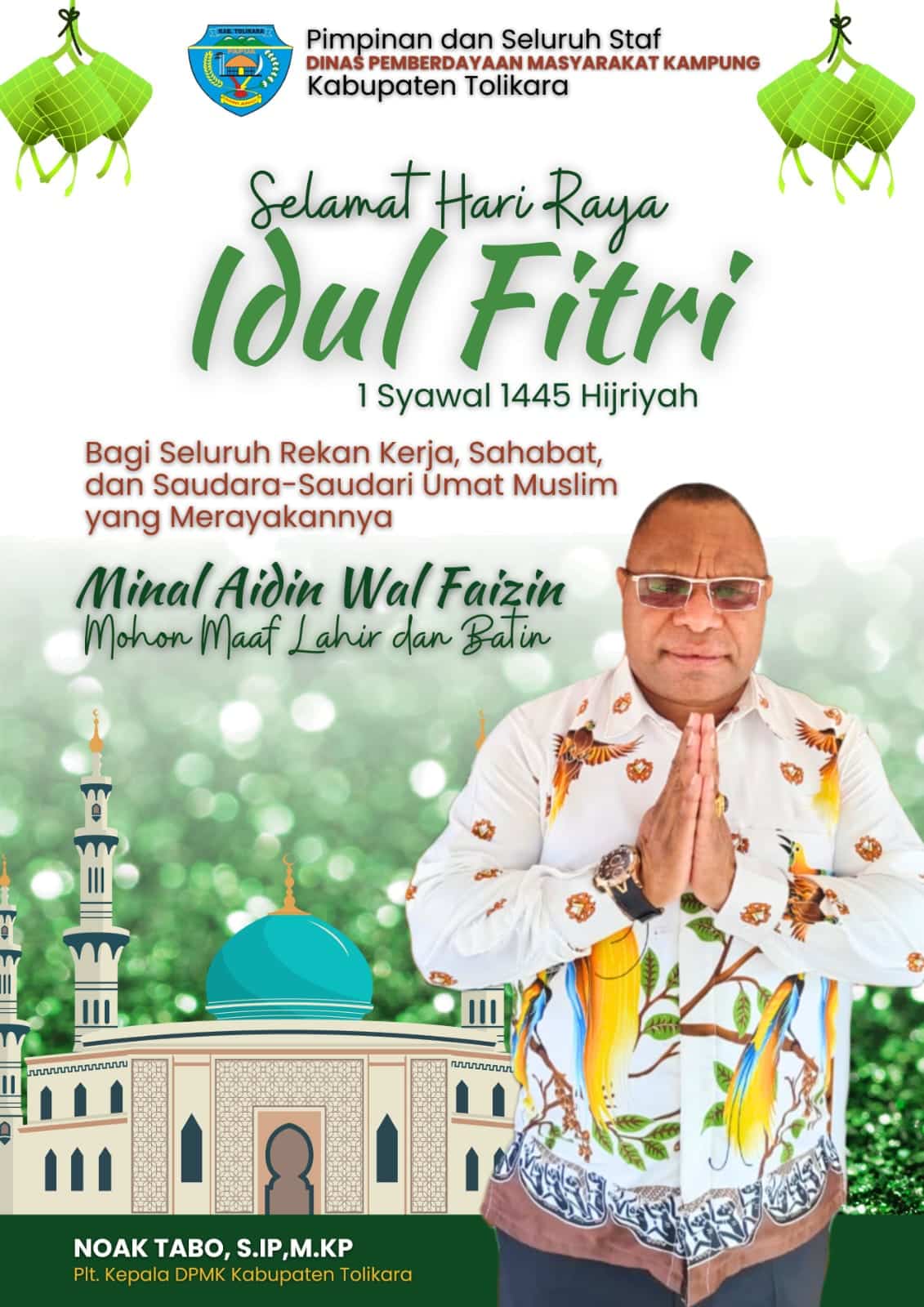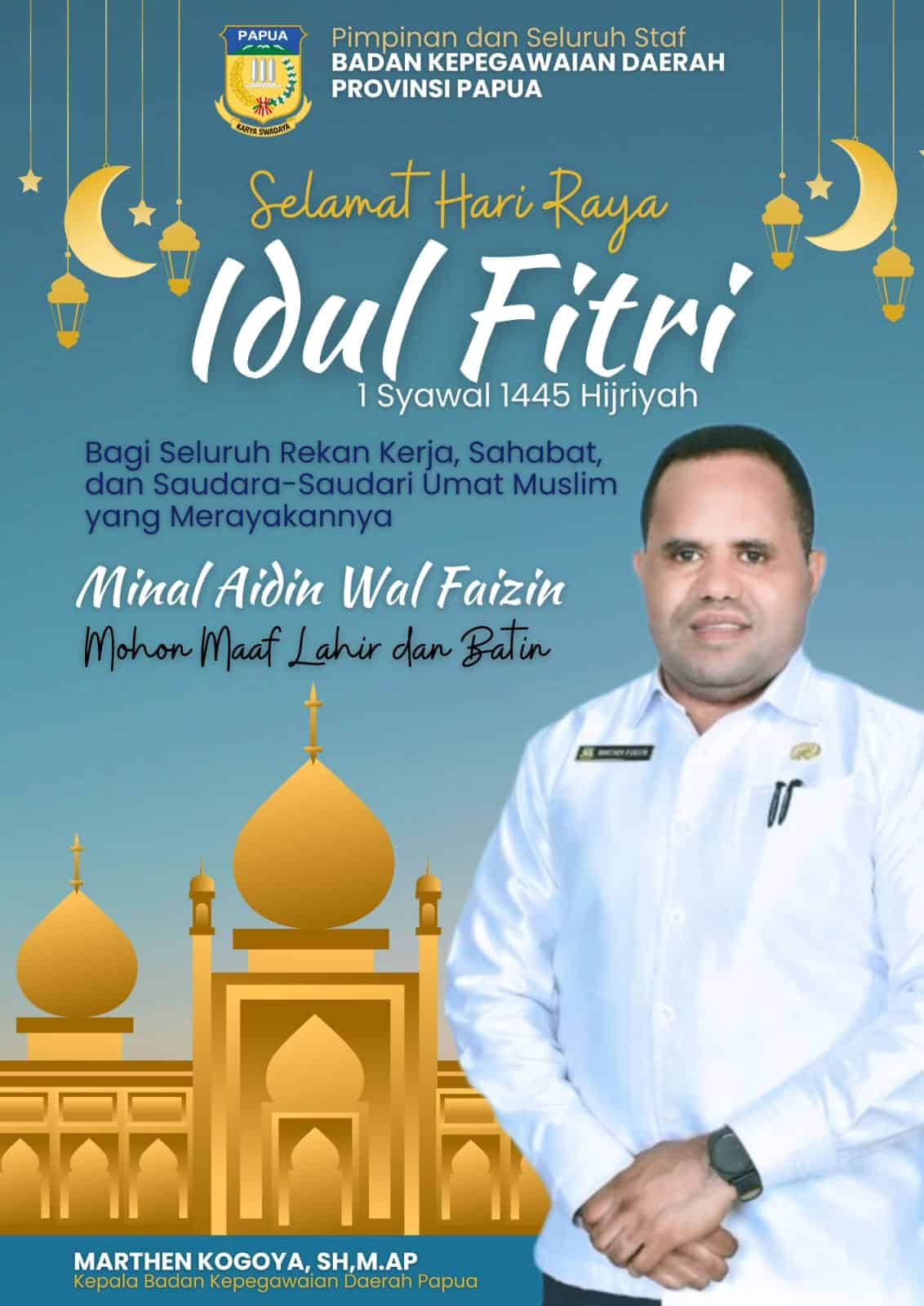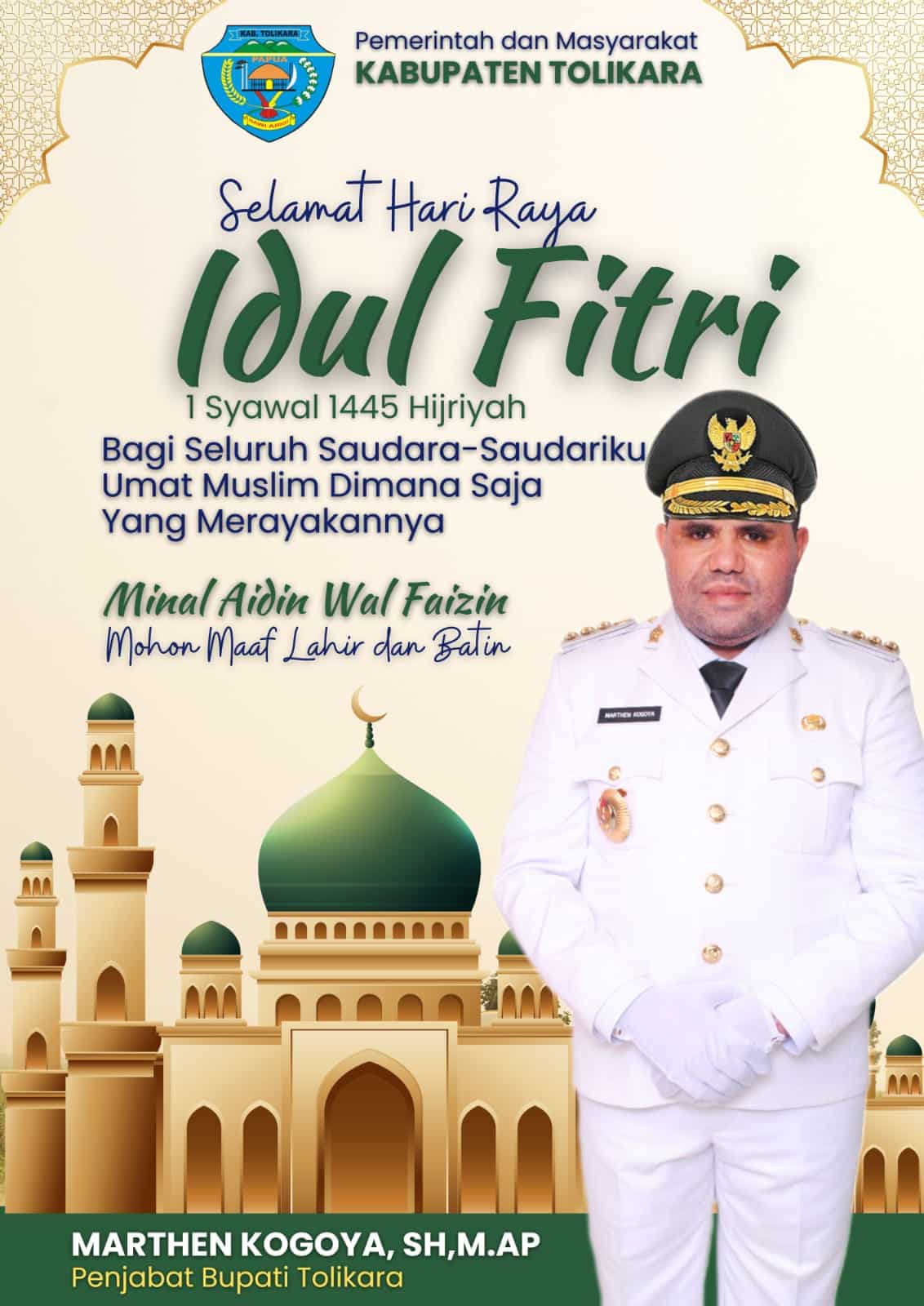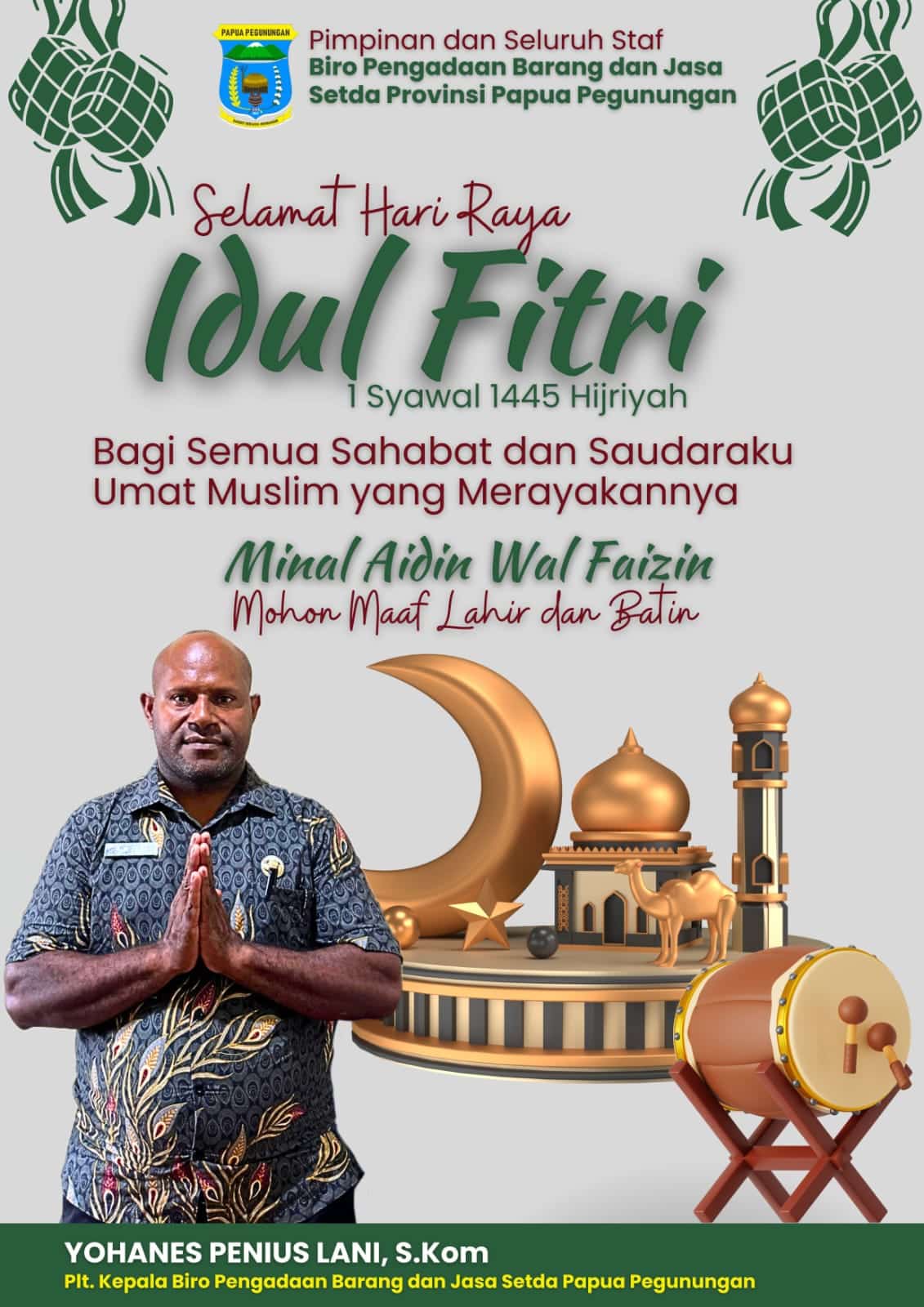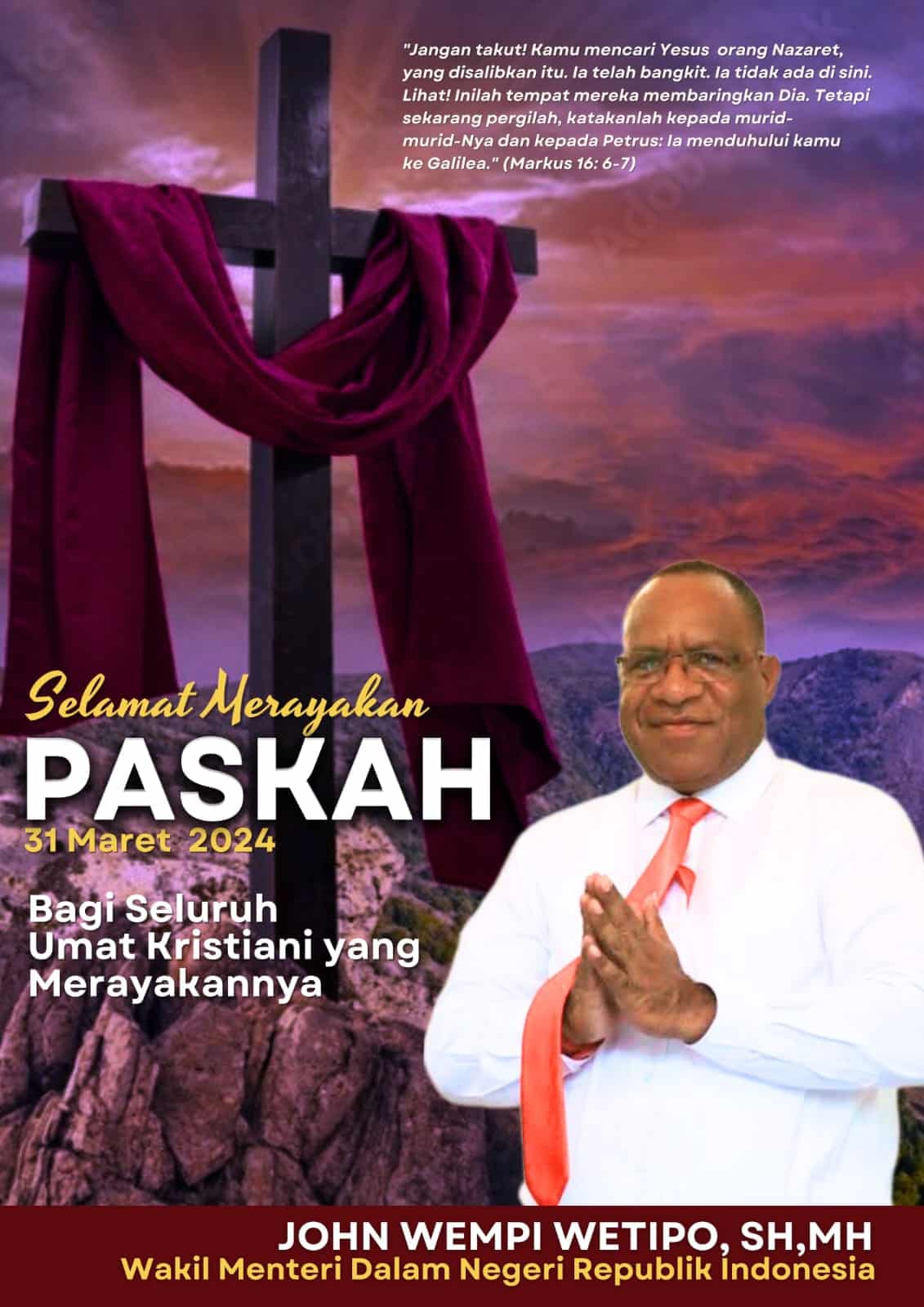PESTA Demokrasi yang mengantar Anies dan Sandy menduduki kursi orang nomor satu dan dua DKI 2017 lalu masih menyisakan kegelisahan. Betapa tidak? Justru di kota metropolitan seperti Jakarta, politik identitas mendapat ruang dan berhasil “memorakmorandakan” kehidupan bersama yang telah lama terbina. Gerakan itu berupa penyebaran berita palsu atau hoax, ujaran kebencian berlatas belakang SARA. Dan naifnya, gerakan tersebut dimotori oleh sejumlah kaum cendikia.
Karenanya, kita patut mengapresiasi keberhasilan Polri yang menciduk sebuah kelompok sindikat penyebar ujaran kebencian atau isu SARA dan hoax di media sosial. Kelompok ini bernama Saracen. Polri mencium adanya indikasi keterlibatan kelompok ini yang bekerja bawah tanah untuk memenangkan pasangam tertentu pada Pilkada Jakarta, Mei 2017 lalu. Beberapa tokoh juga disinyalir mengalirkan dana ke kelompok ini.
Saracen? Ya, sebuah nama yang unik. Sejumlah literatur menjelaskan, kata saracen dalam bahasa Yunani sarakenoi, bahasa Latin Saraceni dan bahasa Arab syarq. Istilah ini digunakan oleh orang Kristen pada Abad Pertengahan untuk menyebut orang-orang yang tinggal di wilayah padang gurun provinsi Romawi Arabia Petraea dan sekitarnya, yang dibedakan dengan bangsa Arab. Di Eropa selama awal abad pertengahan, istilah ini juga mencakup suku-suku di Arabia. Dalam bahasa Portugis istilah ini biasanya diterapkan secara khusus kepada orang Arab yang mendominasi Semenanjung Iberia.
Pada abad ke-12, saracen menjadi sinonim untuk Muslim pada sastra Latin abad pertengahan, suatu perkembangan yang sudah dimulai beberapa abad sebelumnya di antara orang Yunani Bizantin, sebagaimana terbukti dari dokumen-dokumen abad ke-8. Dalam bahasa-bahasa Barat sebelum abad ke-16, saracen umumnya merujuk kepada orang Arab Muslim.
Dalam sebagian kesusasteraan Zaman Pertengahan, saracen,–yakni Muslim–berkulit hitam, sedangkan Kristen berkulit putih. Chanson de Roland (“Syair Roland”), sebuah syair kepahlawanan Perancis dari abad ke-11, mengaitkan profil kulit hitam dengan saracen secara lebih jauh, dengan menetapkan bahwa warna kulit itu ciri utama saracen.
Tetapi mungkin saja, kelompok penyebar ujaran kebencian dan hoax ini tak bermaksud menghidupkan kembali nuansa perang salib. Bisa saja, ada nama SARA yang merupakan akronim dari Suku Agama, Ras dan Antargolongan yang membuat mereka memilih nama itu. Dan jika demikian, saya mememilitir saracen menjadi SARA CENTIL. Sebab fakta menunjukkan bahwa di tengah kekayaan Indonesia atas beragam budaya, suku, dan agama yang dimilikinya, mempersoalkan SARA yang seharusnya sudah final, hanya dilakukan oleh orang-orang centil, suka usik, dan tak ingin Indonesia damai.
Memang harus diakui, politik identitas masih kuat mengakar dalam tubuh bangsa ini. Ketika perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa menjadi jargon membangun ke-kita-an. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.
Hal ini mudah dilihat pada setiap pesta demokrasi. Tak hanya Pilkada DKI Jakarta. Di hampir seluruh pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, politik identitas menjadi senjata mendulang dukungan suara. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom misalnya. Kecenderungan pasangan calon walikota/bupati menggandeng non muslim atau pendatang seakan sudah harga mati. Di NTT pun sangat kental. Sudah menjadi rahasia umum, strategi untuk mendapatkan dukungan menjadi gubenur dan wakil gubernur NTT, sejak dulu terbangun dua dikotomi yang katanya, menjadi rumus memenangkan pertarangun, yakni Flores yang Katolik dan Timor yang Protestan.
Lain di Papua. Lahirnya tokoh politik baru dari Pegunungan Tengah Papua, Lukas Enembe, ketika memenangkan Pilgub Papua 29 Januari 2013 menggandeng Klemen Tinal, menghapus dikotomi politik Pantai dan Gunung yang dipelihara sebelumnya. Saya tertarik dengan jargon Lukas “Kasih Menembus Perbedaan”, yang tak hanya didengungkan tapi juga dipraktikkan dalam pemerintahannya. Salah satunya, pembagian kekuasaan birokrasi. Ketika para biroktat mumpuni dari semua suku dan agama ditempatkan secara merata. Kelompok pendatang dan asli Papua dirangkul untuk saling mengisi. Ini sepikiran dengan Klemen Tinal, yang pada setiap kesempatan, selalu mendengungkan pikiran nasionalisnya: komitmen menjaga toleransi dan pluralisme di Papua.
Tanggal 29 Desember, LUKMEN telah dideklarasikan untuk maju bertarung di Pemilihan Gubernur periode kedua, Juni 2018 mendatang. Rakyat Papua butuh pemimpin seperti keduanya, yang merangkul mereka dalam kesederhanaan. Bukan menggenggam saat kampanye dan menceraiberaikan saat memimpin. Sebagai rakyat Papua yang cerdas, mari kita melawan kampanye berbau suku dan agama, dikotomi gunung pantai, dan sikap gemar menyerang pribadi berlabel argumentum ad hominem. Jangan biarkan isu SARA nan centil, kejam, dan destruktif mendapat ruang dalam pesta yang kita rayakan tahun 2018 mendatang. Kita tentu sepakat akan hal ini.* (Gusty Masan Raya)