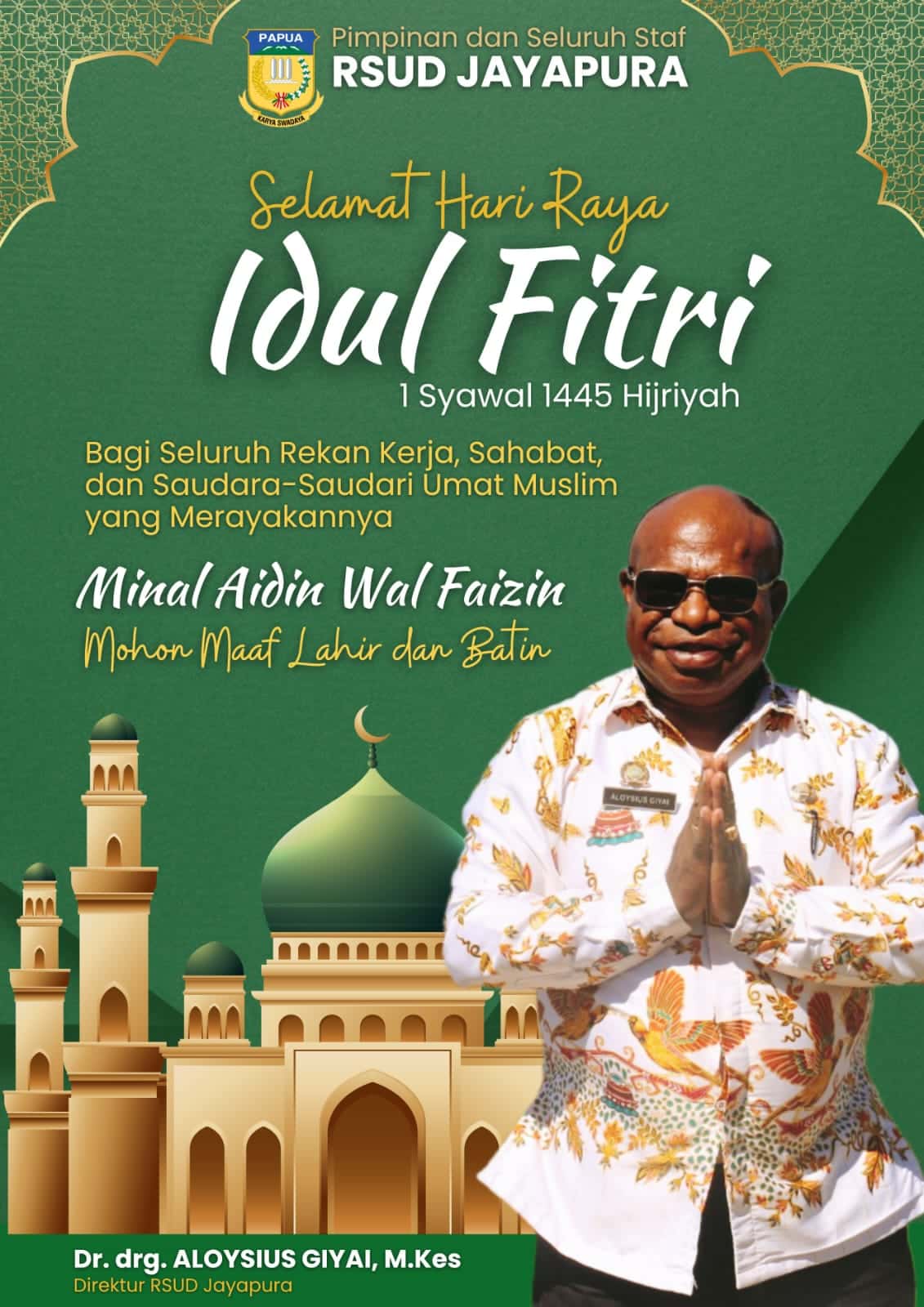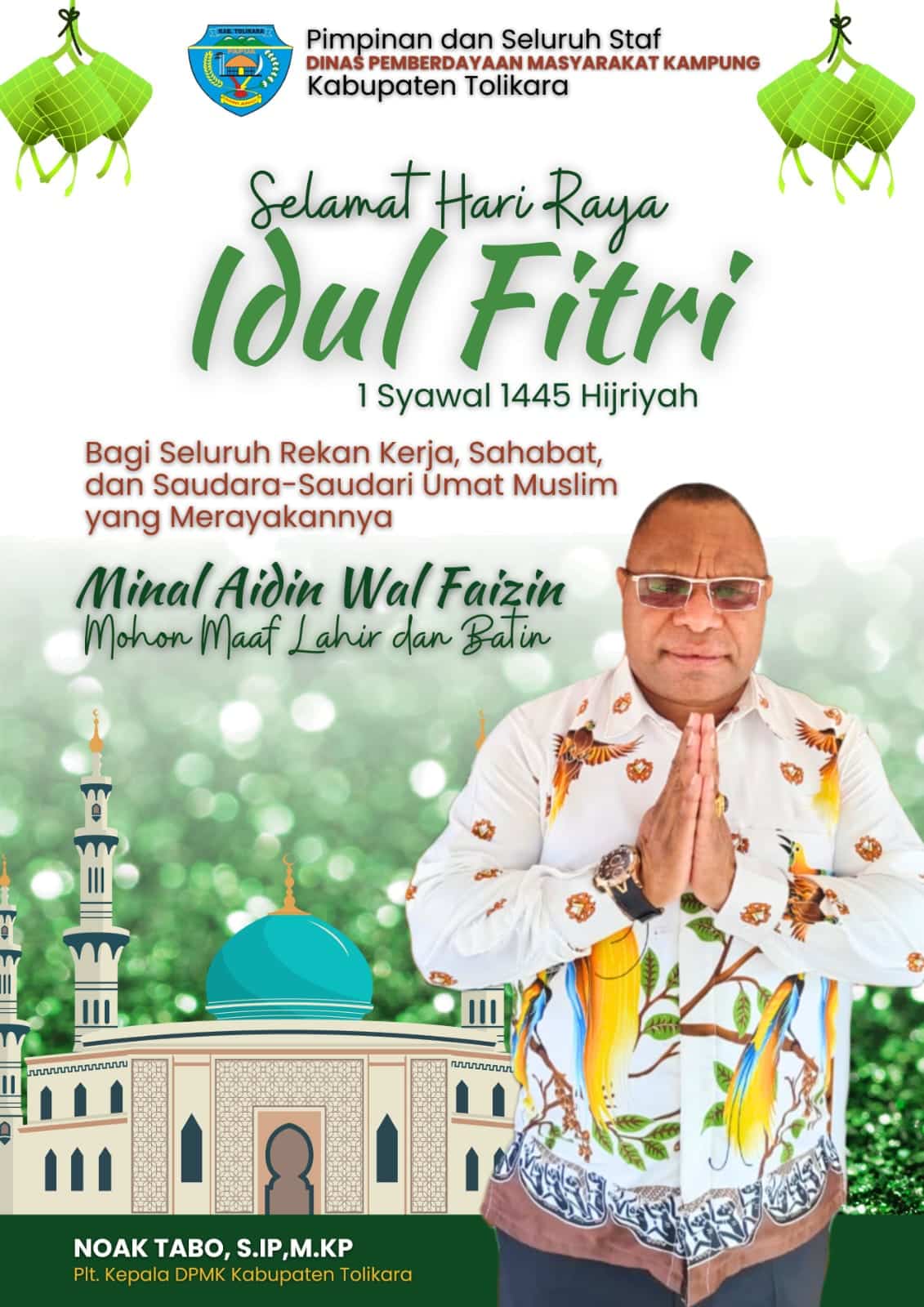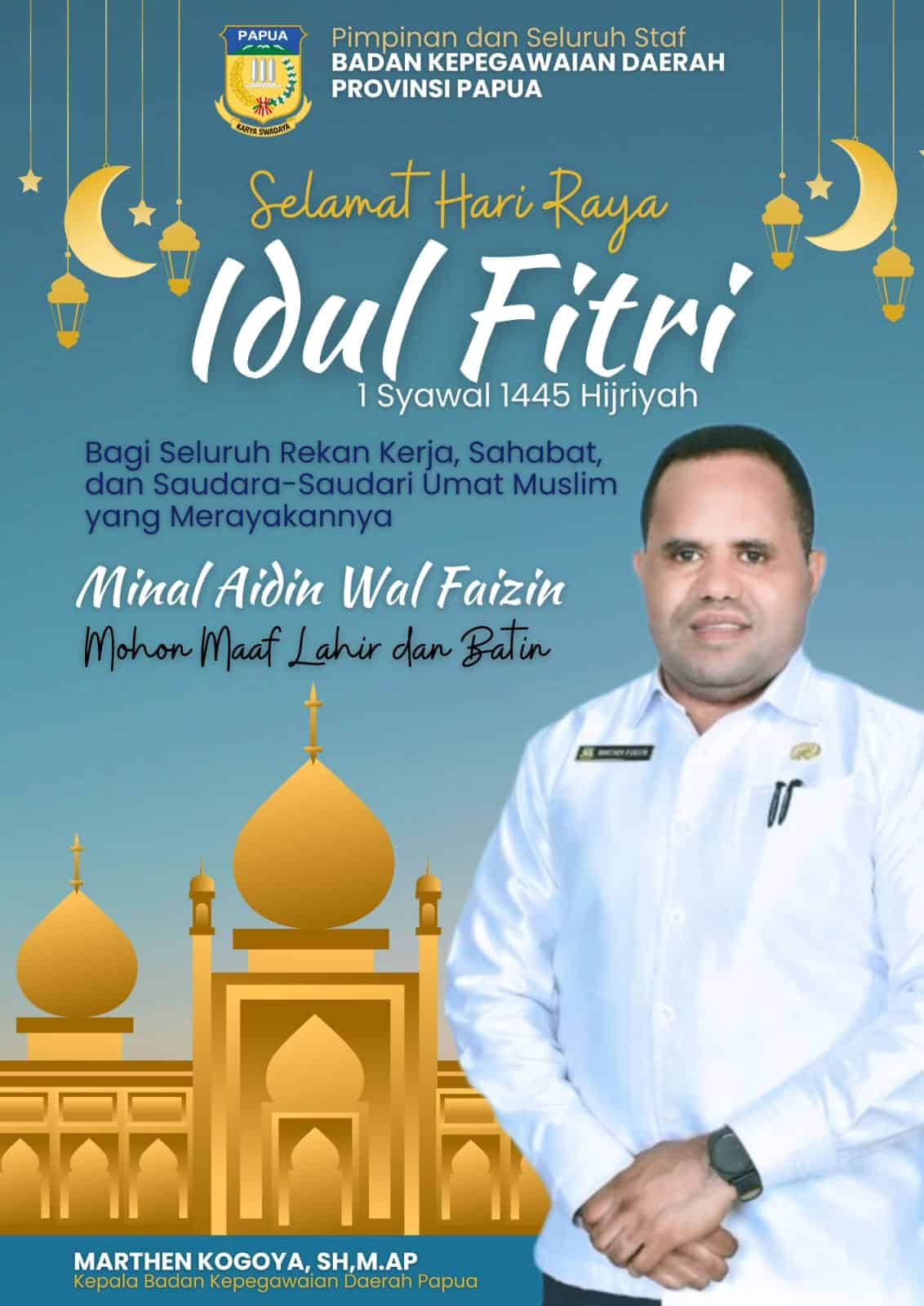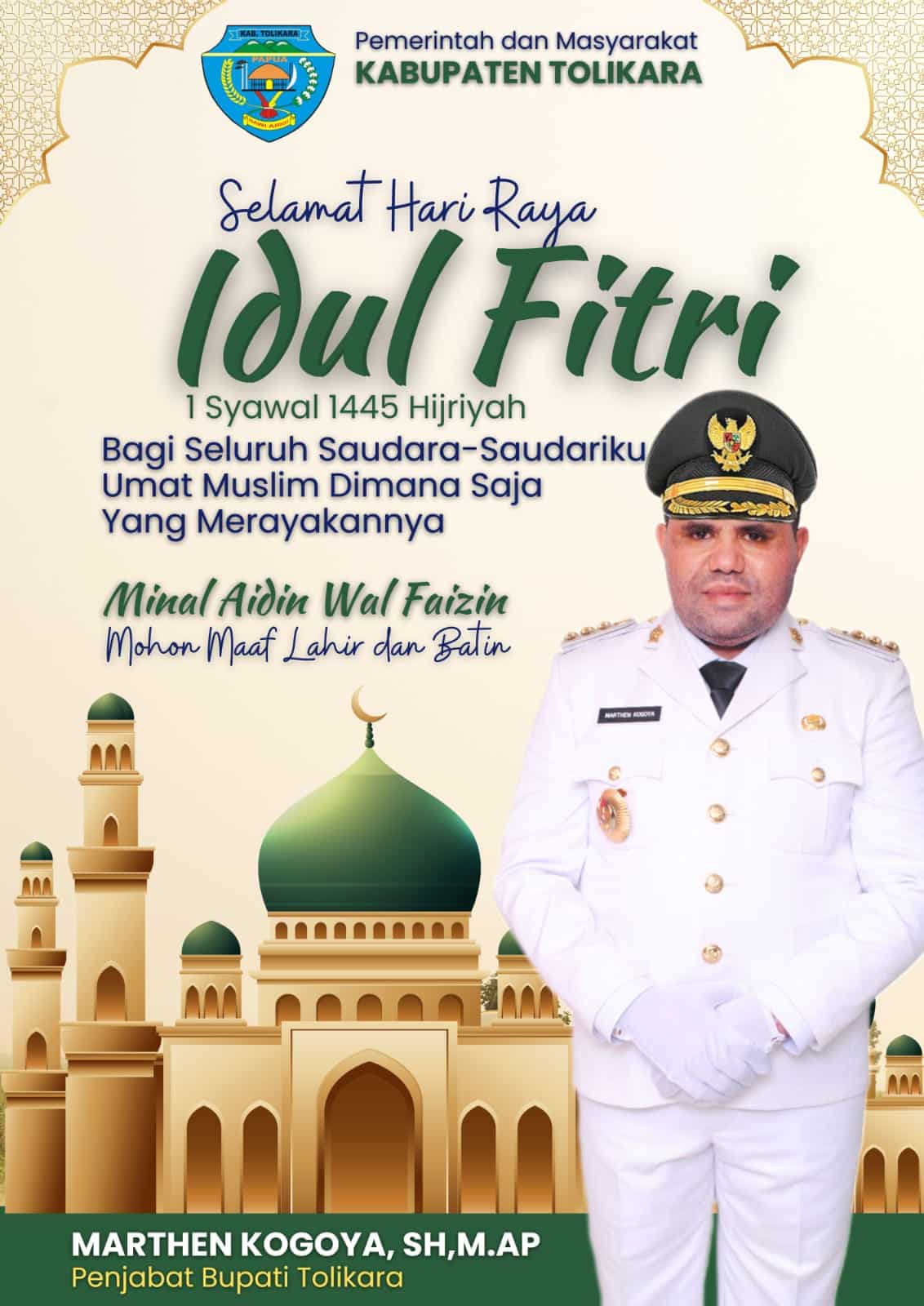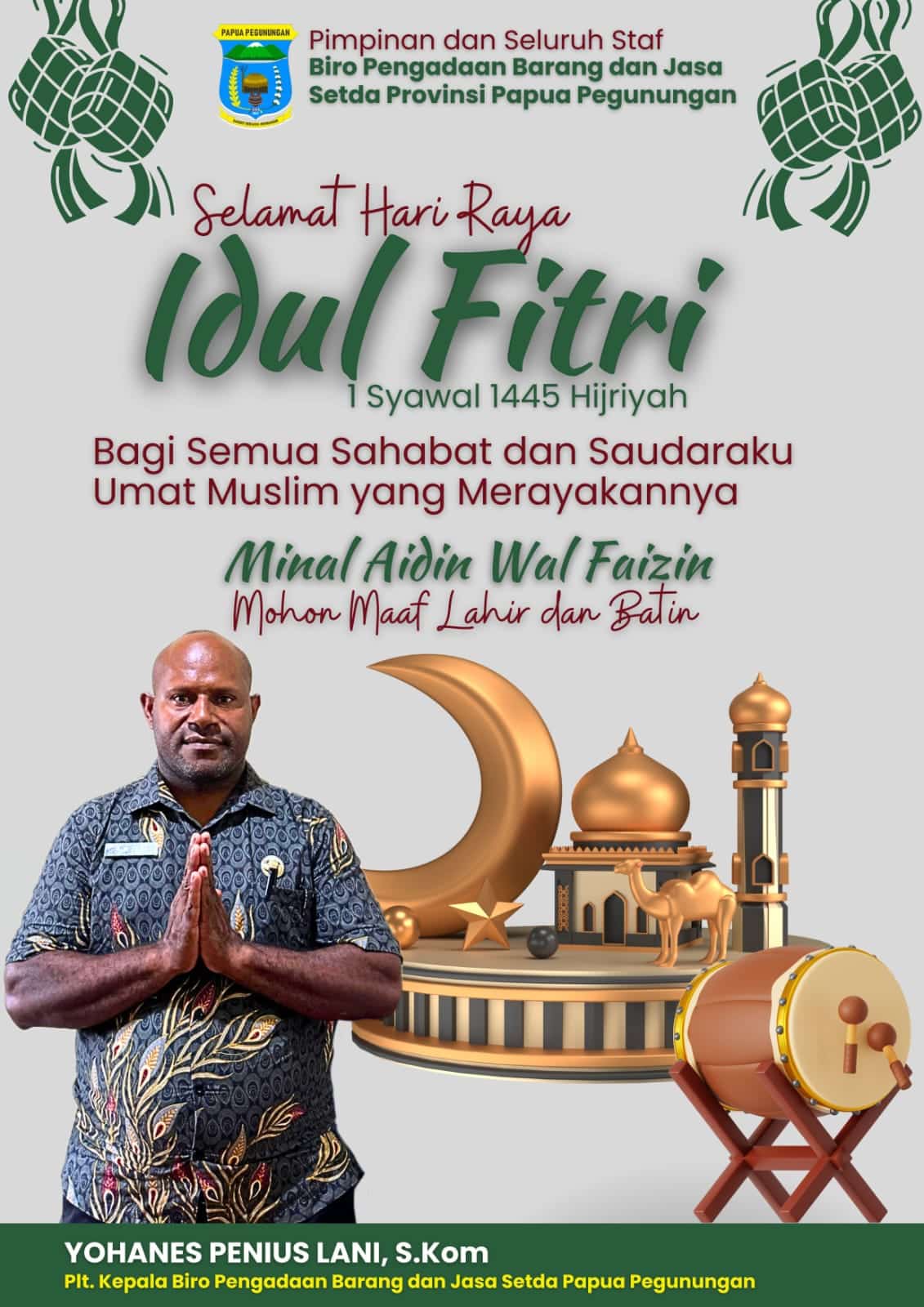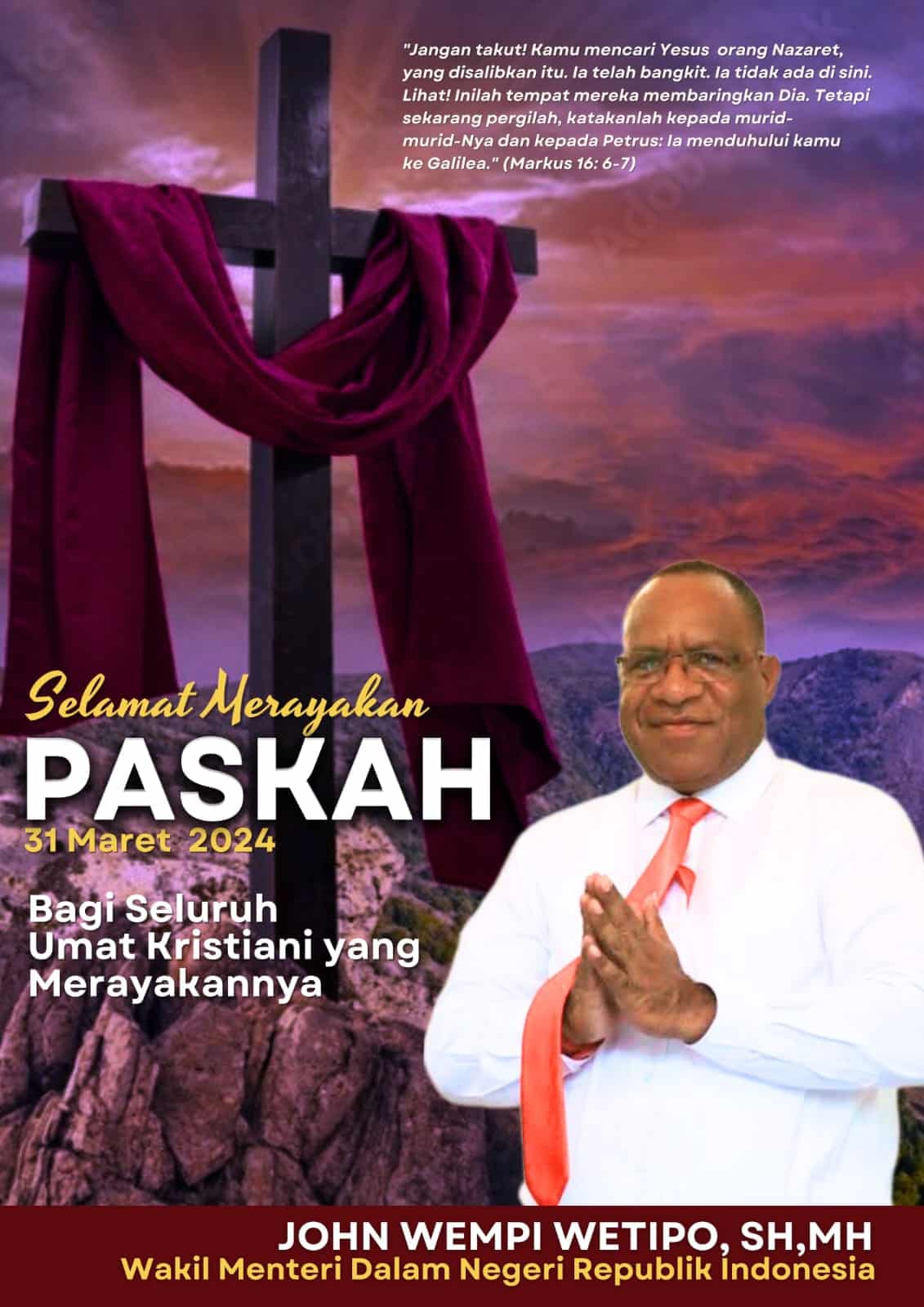SESUATU yang kita namai selalu saja memberi nilai bagi hidup kita. Tetapi itu tak cukup untuk berhenti pada nama belaka, jika makna sesungguhnya tak pernah terwujud. Bahkan, ia hanya bisa muncul dalam mimpi buruk kita, ketika nama itu tak memberi harga apa-apa pada dirinya, kecuali kehampaan. Demikian pesan moral yang hendak disampaikan Umberto Eco lewat novelnya The Name of the Rose. Novel yang terbit tahun 1983 ini berhasil menjadi salah satu karya best seller terkemuka abad pertengahan di Italia. Ketika itu, masyarakat diperhadapkan pada gejalah formalisme semata dan membungkus kualitas hidupnya hanya pada kulit luar.
Umberto Eco lahir pada 5 Januari 1932 dari keluarga besar di Alessandria, kota kecil di wilayah Piedmont, yang beribu kota di Turin—markas klub sepakbola Italia legendaris Juventus. Ayahnya mempunyai tiga belas saudara. Nama keluarga Eco merupakan akronim Latin Ex Caelis Oblatus: Bingkisan dari Surga.
Eco semula dianggap gila. Kegagalan cita-citanya menjadi pengacara—sebagaimana diimpikan ayahnya Guilio di tengah menjamurnya mafia di Italia—tak terpenuhi. Satu pesona dalam diri yang baru saja disadari Eco beberapa tahun sesudahnya ialah kecintaannya akan filsafat dan sastra. Eco akhirnya memenuhi kerinduan ayahnya dengan cara lain: menulis karya sastra untuk membongkar kejahatan.
Nama Eco kian bersinar sebagai novelis kontemporer dunia ketika tiga tahun sesudah terbit, The Name of the Rose sukses diadaptasi sebagai film pada 1986 arahan Jean-Jacques Annaud, dibintangi Sean Connery sebagai William of Baskerville dan Christian Slater sebagai Adso of Melk. William dan Adso ini dua tokoh utama upaya pembongkaran misteri rangkaian pembunuhan brutal yang terjadi di biara di abad pertengahan, persisnya tahun 1327.
Dalam novel itu, kisah mencekam, misterius, dan penuh petualangan detektif diarahkan untuk memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi akibat mafia bisnis. Uang ditampilkan sebagai bentuk kegamangan nilai yang meracuni akal sehat dan moral dari masyarakat Italia abad itu. “…aku hanya mampu memberi namamu, tetapi aku gagal memberimu nilai yang tepat.” Eco menandai kerancuan moralitas umat manusia atas nilai uang itu dalam simbol mawar.
Semiotika kental sains tentang tanda dan simbol ‘uang dan mawar’ si lelaki ‘Bingkisan dari Surga’ ini disetujui filsuf dan sosiolog George Simmel. Dalam bukunya The Philosophy of Money (Filsafat Uang), Simmel dengan lantang menegaskan bahwa uang bukanlah ’substansi’ yang pada dirinya sendiri bernilai dan karenanya dapat ditukarkan dengan apa saja. Uang pada hakikatnya adalah relasi, yakni relasi pertukaran, yang diwujudkan secara jasmaniah. Uang, dengan kata lain merupakan sebuah simbol dari relasi pertukaran.
Seruan moral ini tampaknya nisbi. Perkembangan ekonomi dan kapitalisme yang ditularkan negara-negara Barat telah meracuni pikiran manusia untuk melihat uang tidak pada makna relasi sesungguhnya. Nilai uang semata-mata dilihat hanya pada besar kecilnya angka saja. Bahwa Rp.100.000,- lebih bernilai daripada Rp.10.000,-. Fakta inilah yang membuat semiotika Eco dan Simmel berada di persimpangan jalan.
Harga sembako dan BBM naik, tarif listrik dan angkot naik, biaya sewa rumah, telpon hingga biaya-biaya besar seperti pendidikan dan kesehatan pun jauh lebih naik lagi. Apakah manusia bertahan dengan gaji kecil dan pendapatan rendah? Tak mungkin. Time is money. Semua orang bekerja mengejar uang, memburu rupiah.
Tetapi ada yang lebih berharga di balik upaya memenuhi kebutuhan mendasar manusia sebagaimana digagas Eco dan Simmel: martabat. Ini mengemuka dalam Ethica Nichomachea dari Aristoteles yang memperlihatkan wajah masyarakat abad ini terkait sikapnya menghadapi uang. Ada sikap seimbang-etis sebagai “sikap murah hati”, ada perlakuan ekses atas uang sebagai “sikap boros,” ada pula yang selalu merasa kekurangan sebagai “sikap pelit.”
Yang murah hati adalah dia yang menempatkan uang pada nilainya yang benar yakni relasi. Bukan soal besar kecilnya angka yang tertera di atas lembaran kertas, tetapi sikap moral untuk berbagi itulah yang membuat harga sepeser pun menjadi sangat berarti bagi yang membutuhkan.
Ini jelas berbeda dengan ‘pemerkosaan’ terhadap makna uang dengan sikap boros, menghambur-hamburkan uang, ketamakan yang berujung pada korupsi, maupun menjual harga diri demi uang. Padahal, segala umat di seluruh penjuru dunia dari agama mana pun membenarkan perkataan Yesus ini: “Jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu.” (Lukas 3: 14). Lalu mengapa kita selalu merasa tak pernah cukup? (Gusty Masan Raya/Diterbitkan di Majalah Papua Bangkit Edisi Juni 2017)